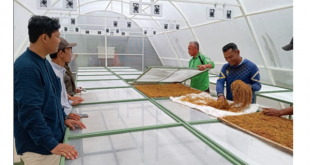Dr. Hartono
(Dosen STAI Sangatta Kutai Timur dan Direktur Esekutif PSS Institute)
DALAM setiap sendi kehidupan berbangsa, perilaku penjabat publik seharusnya menjadi cermin bagi masyarakat. Mereka yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola urusan negara sepatutnya hadir sebagai teladan moral, etika, dan integritas.
Namun, realitas hari ini justru menampilkan potret suram: keteladanan kian redup, berganti dengan sikap elitis, hedonis, koruptif, hingga perilaku yang jauh dari semangat pelayanan publik. Masyarakat kerap disuguhi berita tentang penjabat publik yang terjerat kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau memperlihatkan gaya hidup mewah di tengah kesenjangan sosial yang begitu tajam.
Fenomena ini menciptakan jurang kepercayaan antara rakyat dengan penguasanya. Rakyat merasa tidak lagi memiliki panutan, padahal dalam tradisi politik kita, pemimpin selalu dipandang sebagai figur yang mengayomi, merangkul, sekaligus memberi teladan.
Hilangnya keteladanan juga tampak dari perilaku sehari-hari sebagian pejabat. Alih-alih tampil sederhana dan dekat dengan rakyat, justru yang sering terlihat adalah sikap pamer, bahasa politik yang kaku, serta keputusan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
Sikap seperti ini tidak hanya mencoreng citra institusi negara, tetapi juga melemahkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Padahal, keteladanan seorang pejabat publik bukan sekadar urusan moral pribadi, tetapi juga faktor penting dalam membangun legitimasi.
Ketika pejabat menunjukkan konsistensi antara ucapan dan tindakan, masyarakat akan lebih mudah percaya, bahkan rela berkorban demi mendukung kebijakan negara. Sebaliknya, jika pejabat lebih sering memperlihatkan wajah arogansi dan kepentingan pribadi, legitimasi mereka akan runtuh, dan rakyat memilih untuk bersikap apatis.
“Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Mereka diwajibkan untuk melaksanakan asas penyelenggaraan negara, yaitu akuntabilitas, keterbukaan, kepastian hukum, profesionalitas, dan proporsionalitas. Inilah standar kinerja pejabat publik yang seharusnya mampu dihadirkan sekaligus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”
Lebih jauh, kita tidak bisa menutup mata bahwa sistem politik turut memengaruhi perilaku para pejabat. Budaya patronase, politik transaksional, serta lemahnya sistem pengawasan sering memberi ruang bagi perilaku menyimpang.
Namun, alasan sistem tidak boleh dijadikan pembenaran. Setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat jabatannya. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: pejabat publik yang jujur, transparan, sederhana, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Keteladanan bukan hanya soal tidak korupsi, tetapi juga soal kesediaan mendengar, kesabaran melayani, serta keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum, meski mungkin tidak populer di mata elite.
Momentum untuk memulihkan keteladanan itu selalu terbuka. Reformasi birokrasi, penguatan etika publik, serta peran media dan masyarakat sipil dalam mengawasi pejabat adalah langkah yang harus terus didorong.
Lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dari para pejabat sendiri bahwa jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk menumpuk kekayaan atau memperluas pengaruh pribadi.
Keteladanan pejabat publik bukan hal utopis. Sejarah bangsa ini mencatat banyak figur pemimpin yang rela hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan menolak fasilitas berlebihan. Warisan itu semestinya menjadi inspirasi bahwa menjadi teladan bukan pilihan, melainkan kewajiban.
Hari ini, rakyat menunggu kebangkitan keteladanan itu. Jika pejabat publik terus gagal memberi contoh, maka kepercayaan publik akan semakin tergerus, dan demokrasi yang kita bangun hanya akan tinggal nama.(*)

 PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan
PosKaltim.id Informatif dan Mencerdaskan